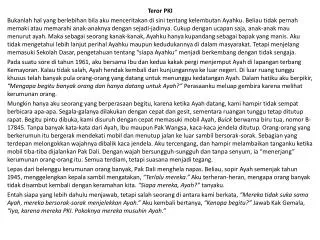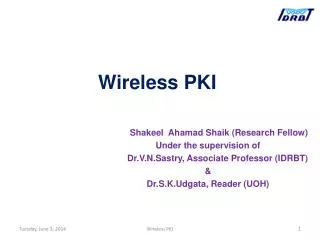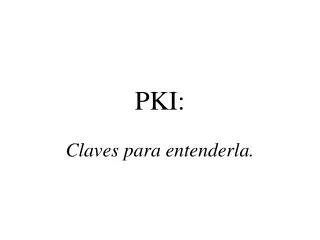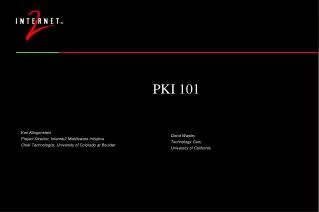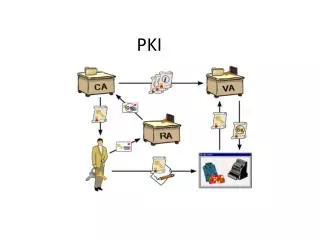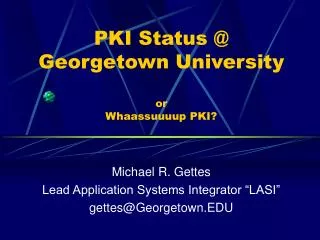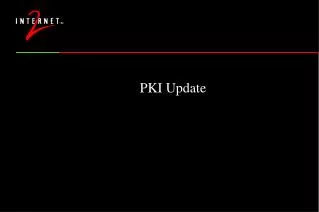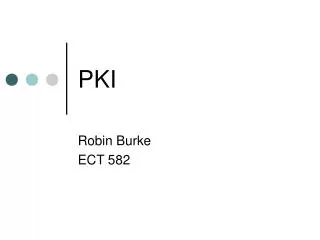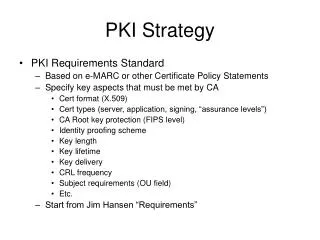Teror PKI
E N D
Presentation Transcript
Teror PKI Bukanlah hal yang berlebihan bila aku menceritakan di sini tentang kelembutan Ayahku. Beliau tidak pernah memaki atau memarahi anak-anaknya dengan sejadi-jadinya. Cukup dengan ucapan saja, anak-anak mau menurut ayah. Maka sebagai seorang kanak-kanak, Ayahku hanya kupandang sebagai bapak yang manis. Aku tidak mengetahui lebih lanjut perihal Ayahku maupun kedudukannya di dalam masyarakat. Tetapi menjelang memasuki Sekolah Dasar, pengetahuan tentang “siapa Ayahku” menjadi berkembang dengan tidak sengaja. Pada suatu sore di tahun 1961, aku bersama Ibu dan kedua kakak pergi menjemput Ayah di lapangan terbang Kemayoran. Kalau tidak salah, Ayah hendak kembali dari kunjungannya ke luar negeri. Di luar ruang tunggu khusus telah banyak pula orang-orang yang datang untuk menunggu kedatangan Ayah. Dalam hatiku aku berpikir, “Mengapa begitu banyak orang dan hanya datang untuk Ayah?” Perasaanku meluap gembira karena melihat kerumunan orang. Mungkin hanya aku seorang yang berperasaan begitu, karena ketika Ayah datang, kami hampir tidak sempat berbicara apa-apa. Segala-galanya dilakukan dengan cepat dan gesit, sementara ruangan tunggu tetap ditutup rapat. Begitu pintu dibuka, kami disuruh dengan cepat memasuki mobil Ayah, Buick berwarna biru tua, nomor B-17845. Tanpa banyak kata-kata dari Ayah, Ibu maupun Pak Wangsa, kaca-kaca jendela ditutup. Orang-orang yang berkerumun itu bergerak mendekati mobil dan menutup jalan ke luar sambil bersorak-sorak. Sebagian yang terdepan melongokkan wajahnya dibalik kaca jendela. Aku tercengang, dan hampir melambaikan tanganku ketika mobil tiba-tiba dijalankan Pak Dali. Dengan wajah bersungguh-sungguh dan tanpa senyum, ia “menerjang” kerumunan orang-orang itu. Semua terdiam, tetapi suasana menjadi tegang. Lepas dari belenggu kerumunan orang banyak, Pak Dali menghela napas. Beliau, sopir Ayah semenjak tahun 1945, menggelengkan kepala sambil mengatakan, “Terlalu mereka.” Aku terheran-heran, mengapa orang banyak tidak disambut kembali dengan keramahan kita. “Siapa mereka, Ayah?” tanyaku. Entah siapa yang lebih dahulu menjawab, tetapi salah seorang di antara kami berkata, “Mereka tidak suka sama Ayah, mereka bersorak-sorak menjelekkan Ayah.” Aku kembali bertanya, “Kenapa begitu?” Jawab Kak Gemala, “Iya, karena mereka PKI. Pokoknya mereka musuhin Ayah.”
Pembicaraan beralih ke soal lain. Ayah bertanya kepada kami mengenai keadaan di rumah sepeninggal Ayah. Tahu-tahu, mobil sudah mendekati rumah kami, dan tiba-tiba saja semua berubah. Tembok pagar rumah kami di Jalan Diponegoro 57, habis dicorat-coret. Pagar batu menjadi kotor dengan tulisan-tulisan yang digoreskan dengan cat putih. Kerumunan menduduki pagar depan rumah kami. Tetapi Ibu sempat bergurau, “Wah, si Wakimin (tukang kebun) bakal repot, ya. Ada pekerjaan tambahan, membersihkan tembok.” Ayah menjawab juga, “Ah, biarkan saja dulu.” Setelah masuk ke dalam rumah, aku bertanya, “Ayah, mengapa mereka benci sama Ayah?” Jawab Ayah, “Iya, karena pikiran-pikiran Ayah berlainan dengan mereka.” Aku bertanya lagi, “Tapi kan mereka rakyat? Kata semua orang di rumah, rakyat senang sama Ayah?” “Ya, tetapi ada juga yang tidak suka. Contohnya mereka itu,” jawab Ayah kembali, sambil memandang kerumunan di luar. Lambat-laun aku mengetahui apa itu PKI. Pengetahuanku tentang kehidupan politik mulai terbuka. Tentunya sangat sederhana, karena aku masih kanak-kanak ketika itu. Pertanyaanku kepada Ayah hanya berputar di sekitar “Siapa dan mengapa.” Ayah menjawab dengan mengambil contoh pengalamannya sendiri. Cerita-ceritanya mudah kumengerti, karena beliau mengikuti daya tangkapku. Rangkaian istilah yang berkaitan dengan kehidupan Ayahku, seperti “Negara Republik Indonesia”, “Pemerintah”, “berjuang”, “penjajahan Belanda”, “Wakil Presiden”, mulai aku pahami. Istilah yang terakhir disebutkan ini aku dapat dari para pembantu rumah tangga yang bekerja pada kami. Mereka selalu bercerita tentang jabatan Ayah dulu, sebelum pensiun. Akhirnya aku juga mengetahui, Ayahku dikenal sebagai “Bung Hatta”. Menurut Ayah, sebutan “Bung” lahir semasa perjuangan dahulu. Dengan sebutan itu, Ayah tidak dianggap jauh lebih tua dari rakyat Indonesia yang sedang berjuang, seperti kaum pelajar, prajurit, serta rakyat di desa-desa. “Halida pun dapat saja menyebut Ayah dengan Bung,” demikian jawab Ayahku. Halida Nuriah Hatta, Pribadi Manusia Hatta, Seri 2, Yayasan Hatta, Juli 2002